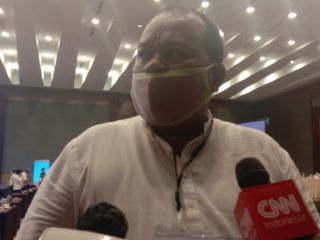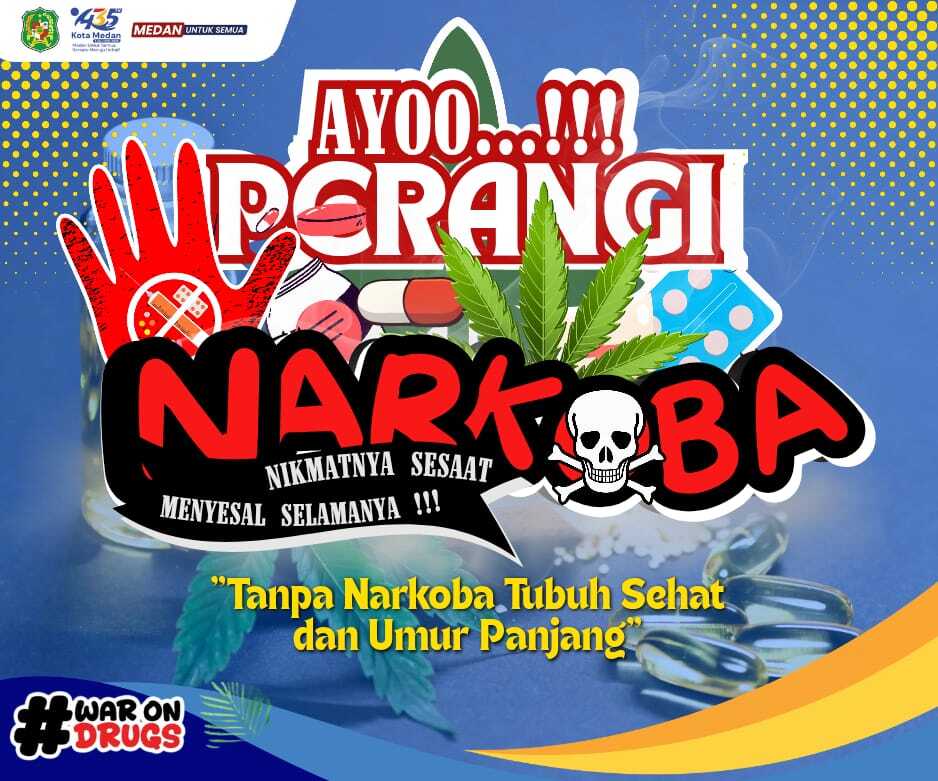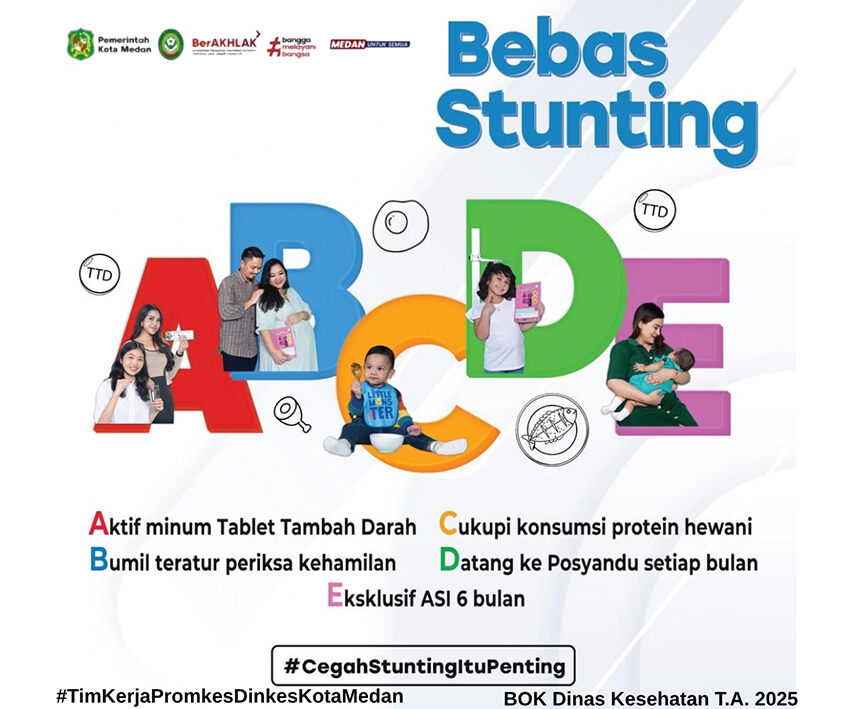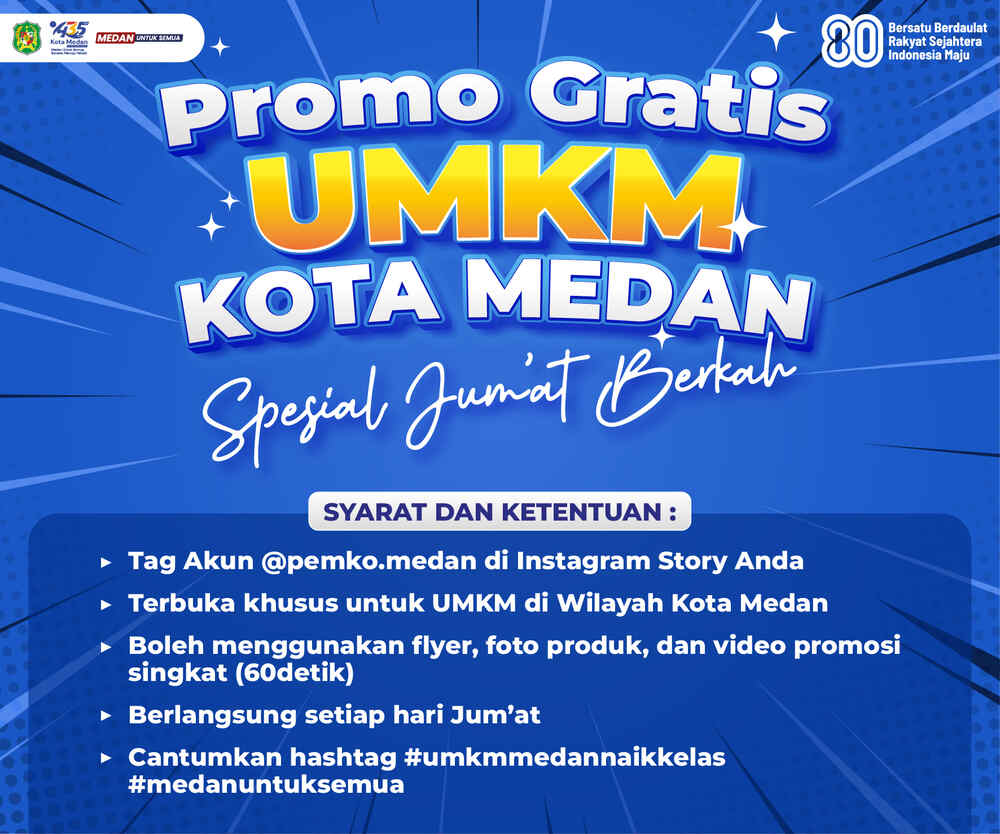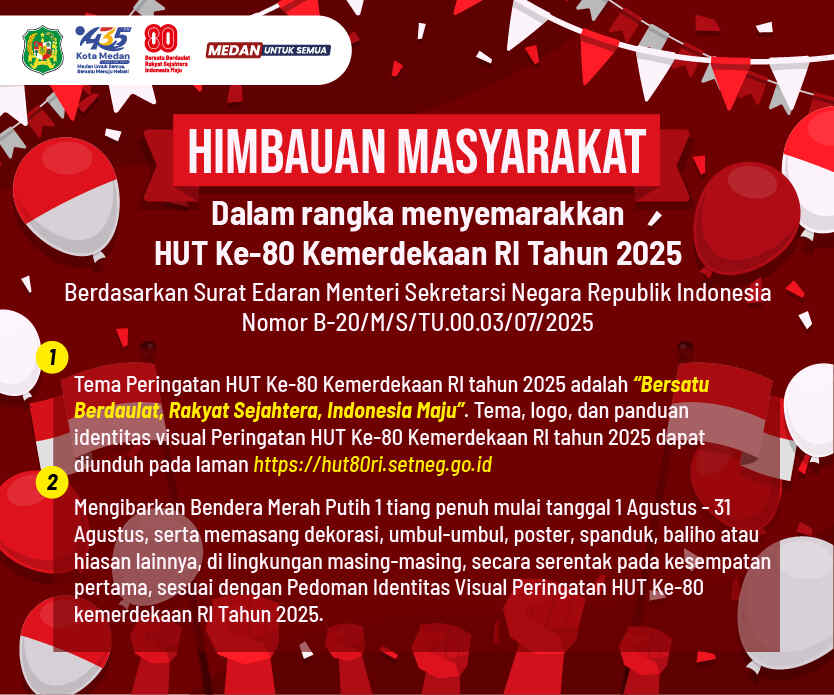Leriadi
Leriadioleh: Leriadi, S.Sos.I
PESANTREN bukan saja lembaga pendidikan agama. Ia adalah akar sejarah dan sumber moral bangsa Indonesia. Sejak masa kerajaan Islam hingga perjuangan kemerdekaan, pesantren telah menjadi benteng perlawanan, pusat pembentukan karakter, dan laboratorium peradaban Nusantara. Kini, di tengah derasnya arus digital dan globalisasi nilai, pesantren kembali dipanggil menunaikan peran historisnya: menjaga jiwa bangsa sambil menuntun arah zaman.
Sejarah mencatat, pesantren hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Di masa kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Mataram, pesantren menjadi pusat pendidikan rakyat sekaligus ruang penyebaran Islam yang damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Para kiai tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan etika sosial, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Ketika kolonialisme datang, pesantren menjadi benteng terakhir perlawanan terhadap dominasi Barat.
Dari rahim pesantren lahir tokoh-tokoh besar seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan Pangeran Diponegoro yang berakar kuat pada tradisi santri. Puncaknya adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945—momen penting yang menegaskan bahwa pesantren bukan hanya bagian dari sejarah keagamaan, melainkan juga bagian dari sejarah berdirinya Republik Indonesia.
Peradaban Islam Indonesia
Pesantren membentuk corak peradaban Islam khas Indonesia: Islam yang ramah, berakhlak, dan berjiwa sosial. Tradisi ngaji, halaqah, dan riyadhah di pesantren bukan hanya latihan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter. Dari lingkungan pesantren tumbuh nilai-nilai keikhlasan, kesetiaan pada guru, gotong royong, dan solidaritas sosial—nilai-nilai yang menjadi fondasi etika publik bangsa Indonesia. Dalam dunia yang semakin materialistis dan kompetitif, nilai-nilai moral dari pesantren justru semakin relevan. Ketika banyak lembaga kehilangan orientasi, pesantren tetap teguh menjaga keseimbangan antara ilmu dan moral, antara kemajuan dan kebijaksanaan.
Abad ke-21 ditandai dengan revolusi digital dan kemajuan teknologi yang luar biasa cepat. Namun di balik kemajuan itu, dunia menghadapi krisis baru: modernitas tanpa jiwa. Manusia semakin terkoneksi secara teknologi, tetapi kian terasing secara spiritual. Masyarakat modern sering kali terjebak dalam pola hidup yang serba instan dan kompetitif, hingga melupakan kedalaman makna dan nilai kemanusiaan. Dalam situasi inilah pesantren menemukan kembali relevansinya.
Pesantren adalah ruang penyeimbang di tengah disrupsi nilai, tempat di mana akal dan hati kembali disatukan. Ia menyimpan apa yang bisa disebut “cadangan moral bangsa,” yakni nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Transformasi Tanpa Kehilangan Akar
Agar tetap relevan di tengah perubahan, pesantren perlu melakukan transformasi. Modernisasi pesantren bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan memperluas makna dan fungsi tradisi itu. Setidaknya, ada empat arah transformasi penting. Pertama, integrasi ilmu agama dan sains modern agar santri tidak hanya memahami teks, tetapi juga konteks kehidupan. Kedua, digitalisasi pembelajaran dan literasi media agar pesantren menjadi produsen konten dakwah yang mencerahkan, bukan sekadar konsumen arus digital. Ketiga, penguatan ekonomi pesantren melalui koperasi dan wirausaha santri. Keempat, diplomasi budaya Islam Nusantara yang memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang damai, moderat, dan beradab kepada dunia. Transformasi ini memastikan bahwa pesantren tidak hanya menjadi benteng masa lalu, tetapi juga mercusuar masa depan.
Jika pada abad ke-20 pesantren menjadi benteng perjuangan kemerdekaan, maka pada abad ke-21 pesantren dituntut menjadi penuntun peradaban digital. Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga arah moral dan kebijaksanaan. Modernitas menuntut kecepatan, tetapi pesantren mengajarkan kedalaman. Zaman menuntut kebebasan, pesantren menanamkan tanggung jawab. Dunia mengejar konektivitas global, pesantren menjaga akar spiritual bangsa. Pesantren tidak menolak kemajuan, melainkan memberi makna pada kemajuan itu—agar manusia tetap menjadi subjek, bukan sekadar alat dari teknologi.
Bangsa Indonesia berdiri bukan semata karena kekuatan politik dan ekonomi, tetapi karena kekuatan nilai dan spiritualitas. Pesantren adalah salah satu mata air utama dari kekuatan itu. Kini, di tengah dunia yang kian bising dan kehilangan arah, pesantren kembali menjadi harapan: tempat nilai-nilai luhur diterjemahkan ke dalam bahasa zaman.(*)
*)Penulis adalah Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar